Oleh: Dwi Taufan Hidayat
Ketua Lembaga Dakwah Komunitas PCM Bergas, Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PDM Kab Semarang

Di tengah sekolah-sekolah yangg kekurangan pembimbing bahasa Inggris dan ruang kelas yangg bocor, pemerintah justru mau menambah pelajaran bahasa Portugis. Alasannya: untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun publik bertanya, SDM siapa yangg mau ditingkatkan — siswa di pelosok negeri, alias para diplomat yangg sibuk mengurus gambaran luar negeri?
Ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto mengusulkan agar bahasa Portugis diajarkan di sekolah, banyak yangg mengernyitkan dahi. Usulan itu muncul dalam pertemuan dengan perwakilan negara-negara berkata Portugis, yangg disambut dengan antusias oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, kebijakan ini bakal “meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperluas jejaring global” (tvOneNews, 23 Oktober 2025).
Namun, di luar ruang konvensi dan mikrofon yangg berkilau, realitas pendidikan nasional jauh dari semerbak diplomasi. Dalam survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024, lebih dari 62% sekolah negeri di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) tetap kekurangan pembimbing bahasa asing dasar — termasuk bahasa Inggris. Ironis jika di tengah situasi itu, pemerintah justru sibuk menambah bahasa Portugis ke daftar pelajaran wajib.
Antara Diplomasi dan Romantisme Kolonial


Bahasa Portugis, tentu, bukan bahasa yangg asing dalam sejarah Nusantara. Sebelum Belanda, Portugislah yangg pertama kali menjejakkan kaki di Malaka pada abad ke-16, membawa rempah dan gereja sekaligus. Jejaknya tetap tersisa di Ternate, Flores, dan sebagian mini Ambon — tapi tidak pernah cukup kuat untuk dijadikan bahasa diplomasi kebangsaan. Maka, ketika kebijakan ini diumumkan, publik bertanya-tanya: apakah ini kebijakan strategis alias sekadar romantisme kolonial yangg terselip dalam rapat diplomatik?
Menurut laporan Kompas (24 Oktober 2025), Prabowo menilai pengajaran bahasa Portugis bisa mempererat hubungan dengan negara-negara di bawah Community of Portuguese Language Countries (CPLP), seperti Brasil dan Angola. Secara diplomatik, buahpikiran itu tidak salah. Namun dari sisi kurikulum, kebijakan semacam itu memerlukan perencanaan panjang, termasuk penyediaan tenaga pengajar, kitab ajar, dan infrastruktur. Belum lagi, pelajaran bahasa asing di Indonesia sering kali hanya menjadi mahfuz tata bahasa tanpa praktik nyata.
“Ini kebijakan yangg belum menyentuh akar masalah,” ujar pengamat pendidikan dari Universitas Indonesia, Dr. Endang Pratiwi, dalam wawancara dengan Tempo (25 Oktober 2025). Ia menilai wacana bahasa Portugis hanyalah simbolisme politik tanpa kajian akademik yangg memadai. “Kita punya masalah serius dengan literasi dasar. Sebelum menambah bahasa asing, semestinya pemerintah konsentrasi pada keahlian membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia yangg baik,” tambahnya.
Pernyataan Endang mencerminkan keresahan publik. Di ruang-ruang kelas pelosok, pembimbing tetap berjuang dengan papan tulis kusam dan perangkat peraga seadanya. Di kota besar, sekolah swasta berkompetisi menambah bahasa Mandarin, Korea, dan Jepang — bukan Portugis — lantaran relevansinya dengan ekonomi dan lapangan kerja. Tapi di level kebijakan, bunyi teknokrat pendidikan sering kalah oleh bunyi politik luar negeri yangg lebih nyaring.
Realitas Pendidikan vs Politik Simbolik
Menurut Detik.com (24 Oktober 2025), MPR justru memuji pendapat Prabowo sebagai “terobosan dalam peningkatan SDM.” Namun pujian ini menimbulkan ironi tersendiri. Lembaga yangg semestinya menjadi cermin kerasionalan publik justru tampak terburu-buru memberi support tanpa kajian kesiapan sistem pendidikan.
Bahasa Portugis memang membuka jendela diplomasi, tapi apakah dia juga membuka pintu ekonomi rakyat? Di Brasil, bahasa itu menjadi kebanggaan nasional. Di Timor Leste, dia menjadi simbol identitas pascakolonial. Tapi di Indonesia, dengan 718 bahasa wilayah dan literasi nasional yangg terus merosot, memaksakan bahasa baru justru berpotensi memperlebar lembah ketimpangan.
Kementerian Pendidikan, dalam keterangannya yangg dikutip Antara (25 Oktober 2025), menyebut bahwa kebijakan ini tetap sebatas “wacana awal.” Namun sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa banyak “wacana awal” akhirnya menjadi beban struktural tanpa hasil nyata. Dari pelajaran komputer di SD hingga program penguatan karakter, banyak kebijakan lahir dari rapat, bukan dari realitas kelas.
Sebuah laporan Akurat.co (26 Oktober 2025) apalagi mengungkapkan bahwa penerapan bahasa asing baru di sekolah memerlukan biaya lebih dari Rp 3 triliun untuk penyediaan pembimbing dan sarana pelatihan. Jika bahasa Portugis masuk ke kurikulum nasional, maka anggaran itu kudu bersaing dengan kebutuhan dasar lain seperti penghasilan pembimbing honorer dan rehabilitasi sekolah rusak.
Kritikus pendidikan, Darman Hadi, menilai kebijakan ini cermin dari “politik simbolik tanpa prioritas.” Dalam kolomnya di The Conversation Indonesia (26 Oktober 2025), dia menulis, “Ketika sebuah negara lebih sibuk mengajarkan bahasa negara lain daripada menguatkan keahlian bahasanya sendiri, maka arah kebijakannya telah berbelok dari pendidikan menuju pencitraan.”
Antara Bahasa dan Logika Kebijakan
Kata-kata itu terasa menampar. Sebab di kembali semboyan “meningkatkan kualitas SDM”, kebijakan semacam ini sering kali hanya menjadi ornamen diplomasi. Rakyat yangg hidup dalam sistem pendidikan yangg timpang bakal menjadi penonton, bukan peserta dari perubahan.
Sementara itu, sebagian warganet merespons dengan nada sinis. Di media sosial, banyak yangg menulis: “Kenapa tidak sekalian bahasa Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang dijadikan bahasa wajib?” Sindiran itu menggambarkan skeptisisme publik terhadap kebijakan yangg tampak lebih elitis daripada solutif.
Namun bagi elite politik, bahasa adalah perangkat diplomasi. Dan diplomasi, sering kali, lebih krusial dari logika kurikulum. Dalam konteks itu, support MPR terhadap pendapat Prabowo tampak lebih sebagai gesture politik luar negeri daripada strategi pendidikan jangka panjang.
Di ujungnya, publik dihadapkan pada pertanyaan yangg lebih dalam: apakah pendidikan tetap menjadi ruang pembentukan nalar, alias sekadar perangkat legitimasi wacana politik?
Mungkin, sebelum mengajarkan bahasa Portugis, kita perlu memastikan bahasa logika kebijakan sendiri sudah betul terucap. Sebab di negeri ini, sering kali yangg fasih bukan rakyat memahami pemerintah, tapi pemerintah yangg sibuk belajar berbincang dengan cermin. (*)
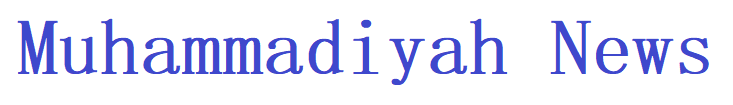
 5 jam yang lalu
5 jam yang lalu











 English (US) ·
English (US) ·  Indonesian (ID) ·
Indonesian (ID) ·